Indonesia
Indonesia
Seorang dokter kapal menyediakan nama bagi Indonesia. Pada 1861,
Adolf Bastian, kelahiran Bremen, Jerman, berlayar di Asia Tenggara. Ia
kemudian menulis sejumlah buku. Salah satunya dibaca banyak orang: Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894. Dari buku ini nama “Indonesia” mulai menandai kepulauan yang ribuan jumlahnya itu.
Bastian berpengaruh karena ia bukan hanya seorang dokter kapal. Ia
lulus ilmu hukum, lulus biologi, ia berminat dalam ilmu yang di zamannya
disebut “ethnologi”, dan ia juga dokter. Bahwa ia jadi dokter kapal,
itu tanda keinginannya menjelajah bagian bumi yang lain. Pada 1873, ia
ikut mendirikan Museum für Völkerkunde di Berlin, dengan koleksi besar
karya manusia dari pelbagai penjuru.
Dokter kapal yang tak henti-hentinya mengarungi laut melintasi batas
ini — dan meninggal dalam perjalanan di usia 80 — yakin bahwa ada yang
menyatukan sesama manusia: “gagasan-gagasan dasar”, Elementergedanken.
Umat manusia, tulis Bastian, “punya segudang gagasan yang dibawa
lahir dalam diri tiap orang,”. Gagasan elementer itu muncul dalam
pelbagai variasinya dari Babilonia sampai dengan Laut Selatan.
Tapi manusia juga menunjukkan Volkergedanken, gagasan yang dikondisikan oleh ruang hidup yang beragam. Bastian menggunakan pengertian Volk, atau dalam bahasa Yunani “ethnos,” untuk menyebut kelompok manusia yang dipertalikan ras, adat, bahasa, nilai-nilai.
Bagi zaman ini, teori Bastian tak lagi menakjubkan. Bahkan pengertian
“ethnos,” juga “ras,” yang jadi tulang punggung teori itu, kini guyah.
Tapi kita bisa bayangkan kuatnya gema pemikiran ini di abad ketika
imperialisme membentuk bumi.
Imperialisme, sebagaimana penjelajahan “etnologi”, (atau
“antropologi”), mempertemukan manusia dari pelbagai asal-usul, namun
pada saat yang sama menunjukkan sebuah jarak — bahkan ketimpangan dan
penaklukan. Dalam imperialisme, sebagaimana dalam karya etnografis,
orang “Barat” bukan menemui melainkan menemukan dunia lain — seakan-akan
“barang” itu ada setelah dilihat oleh “Barat”. Saat itu, “barang” itu
pun beku. Ia berubah jadi “yang-lain” — sebagaimana dalam dongeng
Yunani, manusia jadi batu ketika Medusa menatapnya.
Peralihan dari “liyan” jadi “yang-lain” yang membatu itulah sendi
utama imperialisme. Imperialisme menorehkan sesuatu yang buruk pada
kesadaran: dalam kungkungannya, kata Edward Said, orang jadi yakin bahwa
dirinya semata-mata “orang putih” atau semata-mata orang “kulit
berwarna”. Imperialisme membuat orang tak sadar bahwa orang bukan hanya
satu identitas, tapi punya sejarah yang membuatnya tak sepenuhnya ajeg,
utuh, dan tunggal.
Dalam sejarah itu juga berlangsung dialektik antara temu dan takluk.
Orang berada di satu ruang hidup, tapi dalam posisi yang satu tunduk,
yang lain bertahta. Pertemuan bukan lagi pertemuan, melainkan
penaklukan. Di ruang politik yang sama itu mereka tak saling menyapa —
bahkan dalam hidup sehari-hari.
Dalam A Certain Age, catatan-catatan yang disusun secara
menarik oleh Sejarawan Rudolf Mrazek dari wawancaranya dengan generasi
tua Indonesia, kita tahu bahwa dulu, di kota-kota kita, penduduk Belanda
hadir tapi dengan jarak.
“Waktu saya anak-anak,” cerita Nyonya Surono, “saya tak pernah ketemu orang Belanda di jalan.”.
Pak Mewengkang berkisah tentang masa kecilnya di Sulawesi Utara.
“Saya besar di dusun, dan tak ada orang Belanda di sana. Hanya, pada
hari Minggu, kadang-kadang….seorang pastur Belanda datang”.
Wartawan Rosihan Anwar hanya sedikit berbeda. Di masa kecilnya di
Agam, Sumatra Barat, ayahnya kenal orang Belanda: seorang kontrolir yang
datang ke rumah tiap Lebaran. Hanya tiap Lebaran. Si anak cuma boleh
melihat dari jauh. Sementara Pak Oey, yang besar di Surabaya dan
Batavia, cuma melihat orang Belanda di kolam renang.
Willem Frederik Wertheim, sarjana Belanda yang dikenal sebagai
cendekiawan antikolonialisme, juga mengalami jarak itu. Ia baru tahu ada
yang tak beres di sekitarnya ketika pembantunya bercerita bahwa anaknya
mati karena tak ada yang mengobati sakitnya.
Zaman itu adalah zaman diabaikannya apa yang universal dalam diri
manusia; Elementergedanken Bastian pelan-pelan dilupakan. “Liyan” tak
lagi berarti “sesama”.
Itu sebabnya racun imperialisme jadi menyengat ketika konteksnya
bergeser. Kita ingat riwayat Soewardi Soerjaningrat. Juli 1913 ia
menulis di sebuah koran mengecam pemerintah kolonial yang hendak
merayakan kemerdekaan Belanda dari kekuasaan Prancis. Soewardi
mengandaikan diri sebagai seorang Belanda yang tahu diri dan berseru,
“aku tak akan membuat pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas
kemerdekaannya”.
Sesungguhnya Soewardi menegaskan apa yang universal dalam sesama:
semua ingin merdeka, terutama orang-orang jajahan. Tapi itulah yang tak
diakui pemerintah kolonial. Soewardi ditangkap. Dalam umur 14, ia
diasingkan ke Belanda.
Tapi justru di sana, di negeri dengan kehidupan demokratis itu, ia
kian sadar bahwa “liyan” adalah “sesama” dan “sesama” bisa berarti
“setara”. Dialektik antara temu dan takluk bergerak: jika di negeri
jajahan temu tenggelam oleh takluk, di Eropa yang merdeka takluk
tersisih oleh temu. Pembangkangan Soewardi kian tegas. Perlakuan hukum
yang sama di masyarakat Belanda mengukuhkan keyakinannya bahwa mereka
yang seperti dirinya bukan hamba. Mereka berasal dari sebuah kepulauan
yang tak mau takluk dan jadi “Hindia Belanda”.
April 1917, di halaman Hindia Poetra, Soewardi memilih nama yang
dipakai Bastian bagi tanah airnya. Indonesia: negeri yang dibangun oleh
yang universal, untuk semua, dan sekaligus oleh yang berbeda.
Kutip dari "Catatan Pinggir" oleh Goenawan Mohamad
Kutip dari Catatan Pinggir oleh "Goenawan Mohamad".
Kutip dari "Catatan Pinggir" oleh Goenawan Mohamad
25 Mei 2015
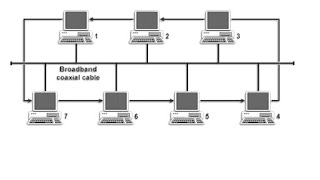
Comments
Post a Comment