Selebritas
Selebritas
Seorang selebritas, atau pesohor, adalah seorang yang terasing dari
cermin di hadapannya. Ia tak lagi sendirian di kamar mandi. Kini
cerminnya digantikan alat lain: kamera, alat perekam suara, atau catatan
seorang jurnalis. Alat-alat itu mewakili tatapan orang banyak yang ia
asumsikan senantiasa hadir. Di tatapan itulah ia melihat dirinya. Atau
lebih tepat: “diri”-nya.
Orang banyak itu — pembaca kolom gosip, pendengar radio, penonton TV
dan bioskop — tentu saja tak tampak di matanya. Ataupun tak jelas benar
sebenarnya siapa sosok dan suara itu. Massa. Kelimun. Orang ramai.
Wajah tanpa riwayat. Bukan “engkau” yang bisa ia ajak bertegur sapa,
melainkan “mereka”. Dan ia berpose untuk “mereka”.
Begitu menentukankah “mereka” yang tak tampak itu, hingga konstruksi
“diri” selebritas seperti Paris Hilton atau Nadia Hutagalung bisa
berbeda dari muka yang di cermin?
Andai kita berada di pertengahan 1930-an, di puncak pertama
perkembangan industri film dan teknologi fotografi, jawabannya lebih
pasti. “Mereka yang tak tampak, yang tak hadir ketika [seorang aktor]
menjalankan pertunjukannya, adalah mereka yang sesungguhnya mengontrol
pertunjukan itu.” Itu kesimpulan Walter Benjamin ketika di tahun itu ia
berbicara tentang tentang penonton, pendengar, dan pembaca media massa
yang tak terlihat oleh sang aktor.
Tapi Benjamin tak sepenuhnya benar. Sebagai konsumen, “mereka yang
tak tampak” itu memang bisa sangat menentukan — mungkin sejalan dengan “the invisible hand” pasar
bebas. Tapi di antara penonton dan sang aktor ada produsen: bukan
hanya sutradara, tapi juga, dan terutama, para pemilik modal yang
menguasai media massa, baik film itu sendiri maupun koran gosip.
Merekalah yang mengedarkan candu itu (gosip adalah candu bagi orang
ramai) hingga orang ramai itu sepenuhnya asyik dalam kekaguman dan siap
menanggung segalanya.
Henry Kissinger – seorang menteri luar negeri yang pintar yang terlanjur jadi pesohor — pernah berkata dengan sedikit mencemooh: “Yang menyenangkan ketika jadi selebritas adalah bila kita membosankan atoledo orang banyak, orang banyak itu menganggap itu gara-gara kesalahan mereka sendiri.”
Tapi Benjamin tak sepenuhnya salah. Di akhir paragaf ia menambahkan
faktor kapitalisme — meskipun lebih tepat tak hanya kapitalisme, tapi
juga tiap bentuk industri budaya yang menjangkau massa, yang mengubah
diri sang aktor jadi “diri”. Padanya sebenarnya tak ada lagi pesona
kepribadian. Pesona itu sudah digantikan “daya pukau yang sudah boyak”,
karena – terutama dalam kapitalisme – pesona itu ada hanya sebagai
komoditas. Pada akhirnya, jika sang pesohor memang punya nilai, ia hanya
punya Ausstellungwert, “nilai-pameran” , “tontonan”, atau “pajangan.”
Kini nilai itu merambat jadi ukuran di mana-mana. Di zaman ketika 90%
informasi yang diserap khalayak Indonesia datang dari TV yang sibuk
dengan pelbagai show, “nilai-tontonan” pun masuk ke dalam
politik: partai-partai dengan sadar mencampur-adukkan peran selebritas
dengan kerja politik. Bintang sinetron TV — pembawa lakon yang
gampangan tapi gemerlap –ramai-ramai diubah jadi calon pemimpin
eksekutif atau anggota dewan legislatif. Dengan keyakinan mereka akan
dipilih. Maksudnya: akan laku.
Cukup mencemaskan. Sebab trend ini mengingatkan kita kepada yang
pernah terjadi di masa lalu, di negeri lain, ketika khalayak dibuat
terpukau dan “sang juara, sang bintang, dan sang diktator muncul sebagai
pemenang.”
Kata-kata itu juga dari Benjamin, di salah satu catatan kaki untuk
risalahnya yang sama, tentang karya seni di masa teknologi reproduksi,
yang ia tulis empat tahun sebelum ia lari dari penindasan Jerman Hitler
tapi berakhir dengan bunuh diri di perbatasan Prancis-Spanyol.
Benjamin berbicara tentang “krisis demokrasi”. Ia menghubungkannya
dengan perubahan kondisi yang menampilkan politisi ke depan publik.
“Radio dan film,” tulisnya, “tak hanya mengubah fungsi sang aktor
profesional tapi juga fungsi mereka yang, seperti politisi, menampilkan
diri di depan media itu.”
Sebuah proses keterasingan pun berlangsung. Sang aktor masuk ke dalam arena politik tanpa subyektifitas, tanpa gelora hati untuk agenda politik yang menuntut darah dan doa. Dua kata itu mungkin terlampau dramatis buat zaman ini, ketika “demokrasi” berubah jadi akrobat dalam tong setan: berputar-putar dengan trampil dari bawah ke atas — sebuah gerak yang akan begitu selamanya. Para pelaku, yang tak punya kata-kata sendiri, akan kehilangan peran bila mereka mendobrak ke luar tong.
Demokrasi-tong-setan ini bisa rapi dan memikat banyak orang. Mungkin ini juga “peng-estetis-an politik,” Ästhetisierung der Politik, yang digemari Hitler dan Mussolini. Tapi ia akan tak mampu menghadapi problem yang mendasar. Di luar tong setan itu, keadilan dan kemerdekaan tiap kali masih terus menerus harus direbut, dengan sengit, dan diperluas. Sementara di dalam,”Parlemen ditinggalkan orang”.
Ketika Benjamin menuliskan kata-kata itu, ia bermaksud menunjukkan bagaimana teknologi mengambil peran dewan perwakilan. Bagi saya, itu berarti politik di parlemen akan jadi kosong dari percakapan dan pergulatan yang berarti. Bukan mustahil sang juara akan tampil dari kekerasan, sang bintang akan datang dari kebosanan, dan sang diktatur dari kedunguan.
Kutip dari "Catatan Pinggir" oleh Goenawan Mohamad
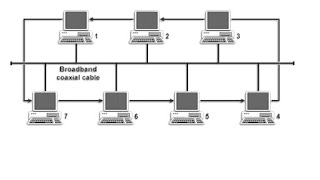
sadappp . (y)
ReplyDelete